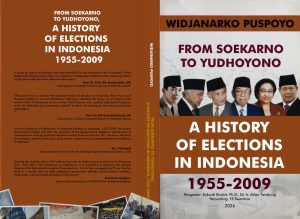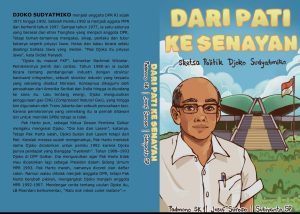Virdika Rizky Utama
Direktur Uksekutif PARA Syndicate dan Dosen Hubungan internasional, President University
Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung menjadi tonggak sejarah bagi negara negara yang baru merdeka dari kolonialisme.
Mereka menyatakan sikap untuk tidak tunduk pada polarisasi Perang Dingin dan memilih netralitas sebagai strategi untuk mempertahankan kedaulatan. Netralitas kala itu adalah bentuk resistensi terhadap logika dominasi, bukan pelarian dari tanggung jawab sejarah. Ia lahir dari tekad untuk berdiri sebagai subyek politik baru di tengah tatanan dunia yang dibelah oleh blok kekuasaan.
Namun, dunia telah berubah. Polarisasi ideologis memang memudar, tetapi struktur kekuasaan global tidak runtuh.
Hari ini, kita menyaksikan transformasi dari dunia bipolar menjadi dunia yang secara semu multipolar. Kekuatan-kekuatan baru memang muncul, tetapi sistem ekonomi politik yang menopang ketimpangan tetap bertahan.
Kapitalisme global tak melemah; ia hanya menyesuaikan diri dengan wajah baru. Dalam lanskap ini, negara-negara Global South tetap terjebak dalam struktur relasi yang timpang dalam perdagangan, teknologi, keuangan, dan narasi.
Perang dagang AS-China yang kembali memanas memperjelas dinamika ini. Presiden Trump menerapkan tarif hingga 145 persen atas produk China dengan dalih melindungi industri domestik dan menanggapi tuduhan keterlibatan China dalam distribusi fentanil ke pasar AS. China membalas dengan tarif 125 persen terhadap produk produk AS.
Konflik ini bukan sekadar pertukaran kebijakan fiskal, melainkan juga perang simbol dominasi dan kontrol terhadap ekonomi dunia. Dampaknya paling dirasakan oleh negara-negara Global South yang tak terlibat langsung dalam pertarungan ini.
Tarif dan sanksi ini menunjukkan bagaimana alat ekonomi digunakan sebagai senjata geopolitik. Negara-negara yang tidak memiliki kekuatan struktural dipaksa jadi penonton dan turut menanggung biaya. Ekspor terganggu, nilai tukar bergejolak, ketergantungan pada pasar besar menjadi pisau bermata dua.
Keberpihakan strategis
Dalam banyak kasus, netralitas justru memperburuk posisi negara berkembang karena membuat mereka tak punya daya tawar menghadapi tekanan eksternal. Dunia yang beroperasi dengan logika sanksi dan tarif sepihak tak menye diakan ruang aman bagi posisi diam.
Kita tak sedang bicara keberpihakan ideologis seperti era Perang Dingin. Hari ini, yang kita butuhkan bukan netralitas, melainkan keberpihakan strategis yang berpijak pada kedaulatan, pembangunan nasional, dan kekuatan domestik. Ini pragmatisme yang dibingkai visi jangka panjang, bukan oportunisme sesaat.
Dalam lanskap hari ini, China telah menjadi mitra yang membuka peluang bagi banyak negara berkembang. Pendekatannya tak mengikat secara politik dan tawarannya sering kali lebih konkret dibanding janji retoris kekuatan lama.
Soft power China hari ini bekerja melalui insentif ekonomi yang tidak disertai tekanan ideologis. Melalui Belt and Road Initiative, lembaga keuangan pembangunan alternatif, dan jarigan dagang digital, China menghadirkan kerangka kerja sama yang lebih cair dibanding lembaga Global North seperti IMF atau Bank Dunia, yang kerap membawa agenda liberalisasi paksa.
Di Afrika, China menggelontorkan lebih dari 4,6 miliar dollar AS hanya dalam setahun terakhir. Sekitar 68 persennya disalurkan ke Angola. Sisanya tersebar di lebih dari 30 proyek di sektor pertanian, energi, manufaktur, dan pertambangan.
Di Asia Tenggara, China memperluas produksi manufakturnya ke Vietnam, Thailand, dan Malaysia, Ekspansi besar juga terjadi di sektor panel surya sebagai respons atas tarif tinggi AS. Di Amerika Latin, China mengamankan proyek kereta api, pelabuhan, dan pembangkit energi dari Brasil hingga Ekuador.
Uni Eropa bahkan terpaksa meluncurkan proyek tandingan, Global Gateway, dengan target 300 miliar euro sebagai respons langsung atas pengaruh China yang kian meluas, bahkan di Eropa.
Manuver ganda
Di tengah realitas ini, strategi yang dibutuhkan oleh Global South bukanlah netralitas yang steril, melainkan kemampuan memainkan manuver ganda. Keterlibatan aktif dengan berbagai kekuatan besar harus dibarengi dengan komitmen menjaga posisi otonom.
Di dunia yang kian saling bergantung, kemampuan mengelola ketergantungan adalah bentuk kekuasaan itu sendiri. Negara seperti Vietnam, Meksiko, atau Turki menunjukkan, posisi geografis dan ekonomi yang rawan bisa diubah jadi keunggulan strategis jika dikelola dengan diplomasi cerdas, diversifikasi mitra, dan kejelasan arah pembangunan domestik.
Ketika negara berkembang mampu merancang hubungan luar negerinya sebagai portofolio dinamis dan bukan relasi satu arah, di situlah kedaulatan mulai terbentuk. Bukan dari penghindaran konflik, melainkan dari kalkulasi yang matang.
Di titik ini, kesalahan terbesar sering bukan pada mitra luar, melainkan pada absennya agenda nasional yang kuat. Banyak negara di Global South masuk ke orbit kekuatan besar tanpa membawa posisi tawar yang jelas. Mereka tidak menawar; mereka menadahkan tangan.
Tanpa perencanaan pembangunan berorientasi kemandirian dan tanpa investasi di riset serta penguasaan teknologi, kerja sama internasional hanya akan melanjutkan siklus ketergantungan. Karena itu, keberpihakan pada China atau siapa pun harus berangkat dari fondasi domestik yang kokoh. Kita tak sedang mencari pelindung baru, tetapi sedang membangun keseimbangan baru.
Global South seharusnya tak hanya jadi penerima pembangunan, tetapi juga perumus narasi global yang baru. Dalam isu seperti transisi energi, keamanan data, dan tatanan keuangan internasional, negara berkembang memiliki peng alaman dan kepentingan yang berbeda dari negara-negara Global North.
Mereka tahu transisi hijau yang dipaksakan tanpa dukungan finansial hanya bentuk baru dari kolonialisme karbon. Mereka tahu arsitektur digital global yang dikendalikan oligopoli korporat—Barat ataupun Timur—hanya akan melanggengkan ketimpangan. Karena itu, saatnya tidak hanya mengatur ulang aliansi, tetapi juga mendefinisikan ulang makna kemajuan dan keadilan global.
Pernyataan netralitas hari ini bukan hanya tak memadai; ia berbahaya. Dunia tak memberi tempat mereka yang memilih diam. Yang tak bersuara akan digantikan oleh suara yang lebih keras. Yang tak menegosiasikan kepentingan sendiri akan dinegosiasikan oleh pihak lain.
Jika pada 1955 netralitas adalah pilihan aktif, pada 2025 netralitas menjadi bentuk keterlibatan pasif di sistem yang tetap berpihak pada kepentingan segelintir kekuatan besar. Pilihan hari ini bukan antara Timur atau Barat, melainkan antara menyerah pada sistem lama atau ikut membentuk yang baru.
Kita tak sedang mencari penjaga baru. Kita sedang mencari ruang untuk menjadi penentu. China bisa jadi mitra strategis berguna, bukan karena mereka tanpa kepentingan, melainkan karena mereka tak memaksakan bentuk tunggal kekuasaan. Namun, tak berarti kita tak punya isi. Kesempatan hanya berguna bagi yang siap mengambilnya. Global South harus datang ke meja global, bu kan sebagai penerima kemurahan, me lainkan pihak yang membawa agenda dan tawaran.
Masa depan dunia tidak ditentukan oleh siapa yang paling kuat hari ini, tetapi siapa paling berani membentuk ulang kekuasaan esok. Dalam proyek ini, netralitas bukan jawaban. Jika Global South ingin menjadi penentu masa depan, mereka harus berhenti menjadi jatar dalam narasi kekuatan lain. Mereka harus mulai menulis cerita mereka sen diri—dengan bahasa mereka sendiri, dan keberanian untuk mengambil posisi.
Tulisan ini dipublikasikan di Kompas.id pada 22 April 2025 dengan judul yang sama.