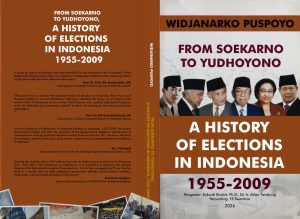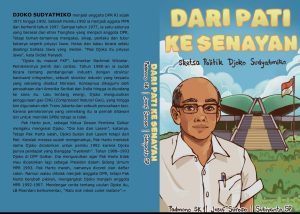Intisari Diskusi Syndicate Update
Senin, 2 Desember 2024
Pikada 2024 telah usai. Namun, patut dicermati bahwa pegelaran ini dibuntuti sejumlah kontroversi, mulai dari nepotisme, intervensi pemerintah pusat dalam mendukung kampanye, hingga keterlibatan “partai cokelat”. Semua upaya kontroversial itu disinyalir untuk memenangkan calon kepala daerah (cakada) yang “dititipkan” oleh elite Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo (Jokowi) kepada pemerintahan baru Presiden Prabowo Subianto. Pemenang kontestasi seolah sudah dipastikan. Tak ayal bila Pilkada kali ini dimaknai sebagai gelaran untuk memperkuat dominasi maupun politik dinasti Jokowi dan Prabowo di tingkat lokal.
Berangkat dari kontroversi itu, banyak pihak yang meragukan roda pemerintahan ke depan akan berjalan demi kepentingan publik. Nasib demokrasi mendatang pun dipertanyakan, di tengah pemaknaannya yang kian direduksi. Satu hal lain yang juga penting, perlu digali bagaimana dominasi Jokowi memengaruhi demokrasi nanti, kendatipun Prabowo merupakan presiden petahana. PARA Syndicate lantas membahas kegelisahan itu dengan menggelar diskusi bertajuk “Setelah Pilkada 2024: Nasib Demokrasi Kita vs Masa Depan Dinasti Jokowi?” di Kantor PARA Syndicate, Jakarta Selatan, Senin, 2 Desember 2024.

Diskusi ini dihadiri empat narasumber yaitu Direktur Eksekutif PARA Syndicate Virdika Rizky Utama, Pakar Hukum Tata Negara dan Pengajar STH Indonesia Jentera Bivitri Susanti, Koordinator Komite Pemilih Indonesia (TePI) Jeirry Sumampow, dan Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ray Rangkuti. Diskusi dipandu oleh Ketua PARA Syndicate Ari Nurcahyo.
Virdika Rizky Utama mengatakan bahwa Indonesia telah lama menjauhi esensi demokrasi dan semakin jauh ketika Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pasalnya, Pilkada yang seharusnya menjadi pintu untuk desentralisasi justru memungkinkan daerah kehilangan otonominya. “Pilkada di banyak daerah dimenangkan oleh pasangan calon yang diusung oleh koalisi elite, yaitu KIM Plus, yang mengarah pada resentralisasi kekuasaan,” tandasnya.
Ia juga menyoroti Pilkada sekadar mengadu endorsemen, alih-alih adu gagasan antar-cakada. Selain itu, Pilkada juga kehilangan keadilan karena pemenangnya hampir pasti bisa ditebak. Bila kondisi ini dibiarkan, kata dia, Indonesia akan kembali ke masa ketika Orde Baru di mana Golkar dan Suharto selalu menjadi pemenang kontestasi. “Ke depan, demokrasi menjadi seolah-olah,” imbuhnya, seraya menambahkan bahwa “hak-hak masyarakat berpotensi diabaikan”.
Lebih lanjut, Virdi mewanti-wanti bila Prabowo selalu tunduk terhadap kepentingan Jokowi. Menurutnya, ini akan membuat Prabowo kehilangan kewibawaannya sebagai presiden di mata publik. “Ini ironi karena ketika kunjungan ke luar negeri Prabowo terlihat kuat dan cakap, tapi di dalam negeri malah tampak tunduk pada Jokowi,” katanya.
Pada kesempatan itu, Jeirry Sumampow—yang berkiprah dalam gerakan pemantauan pemilu sejak 2003—melihat adanya perubahan signifikan dari pemilu silam ke Pemilu 2024. Menurutnya, Pemilu kali ini, yang diikuti Pilkada, merupakan yang tersuram lantaran standard etika dan moral yang semakin buruk.
“Endorsemen kandidat kini dilakukan tanpa malu-malu, politik uang semakin masif, dan netralitas aparatur sipil negara (ASN) diabaikan,” tuturnya. Kondisi ini, kata dia, memungkin calon pemimpin yang tak punya kapabilitas, namun punya modal finansial dan kedekatan dengan elite kekuasaan untuk mencalonkan diri di pemilu.
Jeirry mengatakan bila mereka yang diendorse memenangkan kontestasi, maka mereka akan fokus untuk membayar “hutang” kepada pengendorse. Hal ini kerap kali disusul kasus korupsi, yang sampai saat ini penegakkan hukumnya masih menjadi pekerjaan rumah karena hukum telah menjadi alat kekuasaan. “Dengan pemimpin seperti itu, demokrasi kita akan suram di masa depan,” tambahnya.
Ray Rangkuti turut menambahkan bahwa cakada yang mengandalkan kedekatan keluarga atau hubungan personal dengan figur tertentu untuk memenangkan kontestasi—atau diendorse—belum tentu mumpuni memimpin. Endorsemen ini, lanjutnya, jelas berseberangan dengan narasi atau slogan “mandiri” yang kerap digaungkan pemerintah. “Bagaimana mentalitas kemandirian bisa terbentuk jika calon pemimpin saja terus bergantung pada nama besar keluarga atau kerabat mereka?” pungkasnya.
Lebih lanjut, Ray mengatakan KIM Plus kemungkinan besar akan mendominasi hasil Pilkada. Namun, capaian ini akan membawa kerugian bagi beberapa partai anggota koalisi, seperti Golkar dan PKS, yang kehilangan basis suara di banyak daerah. Di tengah momen ini, katanya, PDI-P lebih solid dan berpotensi menjadi simbol oposisi terhadap pemerintahan Prabowo di masa depan. “Namun, apakah PDIP benar-benar akan mengambil peran tersebut? Kita lihat nanti,” ujarnya.
Meski ada potensi kemunculan oposisi yang mengakomodasi publik, Ray memproyeksikan kebebasan berpendapat akan semakin terancam. Ia menilai Prabowo Subianto, sebagai presiden, kemungkinan tak mampu memberikan perlindungan bagi kebebasan berekspresi. Terlebih melihat sepak terjang sebelumnya. “Kondisi demokrasi kita akan semakin memburuk. Masyarakat semakin takut untuk bersuara,” katanya.
Sementara itu, Bivitri Susanti menyoroti bagaimana demokrasi dimanipulasi melalui cara-cara legal oleh Jokowi, yang berpotensi berlanjut di masa Prabowo. Ia menjelaskan hal itu dikenal sebagai autocratic legalism, di mana semua upaya manipulasi demokrasi yang sudah dilakukan dianggap benar karena legal secara hukum. “Misalnya, Prabowo mengendorse calon tertentu ketika Pilkada, tapi Bawaslu bilang bukan pelanggaran karena endorse itu dilakukan hari Minggu dan presiden libur… ini akal sehat kita dibolak-balik,” tuturnya.
Ia berpendapat hal itu, ditambah menguatnya jaringan oligarki, jika terus dibiarkan akan mengubah persepsi publik tentang demokrasi, membentuk normal (demokrasi) baru, serta memperkuat dominasi elite politik dan oligarki. Imbasnya, “masyarakat akan terdampak langsung, terutama masyarakat marjinal… Lama-lama akan menjadi hutan rimba, hukum rimba di mana yang menang adalah yang kuat secara ekonomi dan jaringan politik.”
Maka dari itu, Bivitri menekankan bahwa masyarakat boleh menolak hukum yang tidak punya dasar moral dan tidak adil. Hukum yang seperti ini kehilangan legitimasinya. “Itu tidak layak kita supreme-kan,” tandasnya, dan memberi contoh seperti UU Cipta Kerja, UU Mineral dan Batu Bara, dan Putusan Mahkamah Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan Gibran Rakabuming Raka menjadi wakil presiden.
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=jZbE7ivJGXE&t=1645s
(Tim PARA Syndicate)